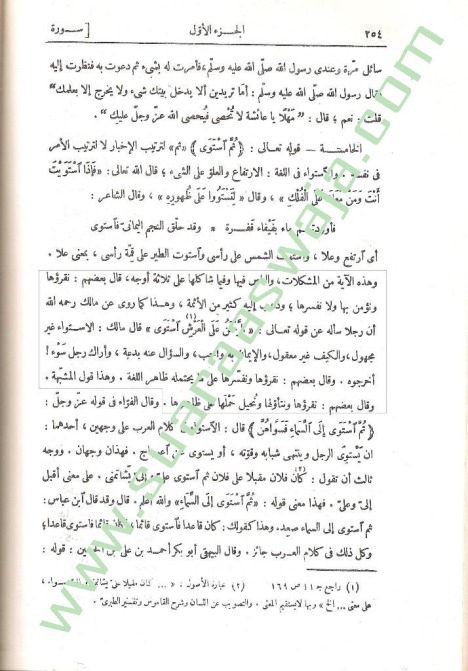Judul : Tafsir Istawa Studi Komprehensif Tafsir Istawa Allah ada tanpa tempat
Penulis : Kholil Abou Fateh
Ukuran buku : 20 cm x 14 cm
Latar Belakang
Al-Hamdu Lillâh Rabb al-‘Âlamîn.
Wa ash-Shalât Wa As-Salâm ’Alâ Rasûlulillâh.
Ada beberapa poin ringkas yang hendak penulis ungkapkan dalam mukadimah buku ini, sebagai berikut:
• Bahwa kecenderungan timbulnya aqidah tasybîh (Penyerupaan Allah dengan
makhluk-makhluk-Nya) belakangan ini semakin merebak di berbagai level
masyarakat kita. Sebab utamanya adalah karena semakin menyusutnya
pembelajaran terhadap ilmu-ilmu pokok agama, terutama masalah aqidah.
Bencananya sangat besar, dan yang paling parah adalah adanya sebagian
orang-orang Islam, baik yang dengan sadar atau tanpa sadar telah keluar
dari agama Islam karena keyakinan rusaknya. Imam al-Qâdlî Iyadl
al-Maliki dalam asy-Syifâ Bi Ta’rîf Huqûq al-Musthafâ mengatakan bahwa
ada dari orang-orang Islam yang keluar dari Islamnya (menjadi kafir)
sekalipun ia tidak bertujuan keluar dari agama Islam tersebut.
Ungkapan-ungkapan semacam; “Terserah Yang Di atas”, “Tuhan tertawa,
tersenyum, menangis” atau “Mencari Tuhan yang hilang”, dan lain
sebagainya adalah gejala tasybîh yang semakin merebak belakangan ini.
Tentu saja kesesatan aqidah tasybîh adalah hal yang telah disepakati
oleh para ulama kita, dari dahulu hingga sekarang. Terkait dengan
masalah ini Imam Ibn al-Mu’allim al-Qurasyi (w 725 H) , dalam kitab Najm
al-Muhtadî Wa Rajm al-Mu’tadî , meriwayatkan bahwa sahabat Ali ibn Abi
Thalib berkata: “Sebagian golongan dari umat Islam ini ketika kiamat
telah dekat akan kembali menjadi orang-orang kafir”. Seseorang bertanya
kepadanya: “Wahai Amîr al-Mu’minîn apakah sebab kekufuran mereka? Adakah
karena membuat ajaran baru atau karena pengingkaran? Sahabat Ali ibn
Abi Thalib menjawab: “Mereka menjadi kafir karena pengingkaran. Mereka
mengingkari Pencipta mereka (Allah) dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat
benda dan anggota-anggota badan”.
• Ada seorang mahasiswa bercerita kepada penulis bahwa suatu ketika
salah seorang dosen Ilmu Kalam mengajukan “pertanyaan” di hadapan para
mahasiswanya, ia berkata: “Benarkah Allah maha kuasa? Jika benar,
kuasakah Allah untuk menciptakan “Sesuatu” yang sama dengan Allah
sendiri?”, atau “Benarkah Allah maha kuasa? Jika benar, maka mampukah
Dia menciptakan sebongkah batu yang sangat besar, hingga Allah sendiri
tidak sanggup untuk mengangkatnya?”, atau berkata: “Jika benar Allah
maha Kuasa, maka kuasakah Dia menghilangkan Diri-Nya hanya dalam satu
jam saja?”. Ungkapan-ungkapan buruk semacam ini seringkali dilontarkan
di perguruan-perguruan tinggi Islam, terutama pada jurusan filsafat.
Ironisnya, baik dosen maupun mahasiswanya tidak memiliki jawaban yang
benar bagi pertanyaan sesat tersebut. Akhirnya, baik yang bertanya
maupun yang ditanya sama-sama “bingung”, dan mereka semua tidak memiliki
jalan keluar dari “bingung” tersebut. Hasbunallâh.
Entah dari mana pertanyaan buruk semacam itu mula-mula dimunculkan. Yang
jelas, jika itu datang dari luar Islam maka dapat kita pastikan bahwa
tujuannya adalah untuk menyesatkan orang-orang Islam. Namun jika yang
menyebarkan pertanyaan tersebut orang Islam sendiri maka hal itu jelas
menunjukan bahwa orang tersebut adalah orang yang sama sekali tidak
memahami tauhid, dan tentunya pengakuan bahwa dirinya sebagai seorang
muslim hanya sebatas di mulutnya saja. Ini adalah contoh kecil dari apa
yang dalam istilah penulis bahwa Ilmu Kalam telah mengalami distorsi.
Padahal, jawaban bagi pertanyaan sesat tersebut adalah bahasan sederhana
dalam Ilmu Tauhid atau Ilmu Kalam; ialah bahwa hukum akal terbagi
kepada tiga bagian; Pertama; Wâjib ‘Aqly; yaitu sesuatu yang wajib
adanya, artinya; akal tidak dapat menerima jika sesuatu tersebut tidak
ada, yaitu; keberadaaan Allah dengan sifat-sifat-Nya. Kedua; Mustahîl
‘Aqly; yaitu sesuatu yang mustahil adanya, artinya akal tidak dapat
menerima jika sesuatu tersebut ada, seperti adanya sekutu bagi Allah.
Ketiga; Jâ-iz ‘Aqly atau Mumkin ‘Aqly; yaitu sesuatu yang keberadaan dan
ketidakadaannya dapat diterima oleh akal, yaitu alam semesta atau
segala sesuatu selain Allah.
Sifat Qudrah (kuasa) Allah hanya terkait dengan Jâ-iz atau Mumkim ‘Aqly
saja. Artinya, bahwa Allah Maha Kuasa untuk menciptakan segala apapun
yang secara akal dapat diterima keberadaan atau tidakadanya. Sifat
Qudrah Allah tidak terkait dengan Wâjib ‘Aqly dan Mustahîl ‘Aqly. Dengan
demikian tidak boleh dikatakan: “Apakah Allah kuasa untuk menciptakan
sekutu bagi-Nya, atau menciptakan Allah-Allah yang lain?” Pertanyaan ini
tidak boleh dijawab “Iya”, juga tidak boleh dijawab “Tidak”. Karena
bila dijawab “Iya” maka berarti menetapkan adanya sekutu bagi Allah dan
menetapkan keberadaan sesuatu yang mustahil adanya, dan bila dijawab
“Tidak” maka berarti menetapkan kelemahan bagi Allah. Jawaban yang benar
adalah bahwa sifat Qudrah Allah tidak terkait dengan Wâjib ‘Aqly dan
tidak terkait dengan Mustahîl ‘Aqly.
• Contoh kasus lainnya yang pernah dialami penulis dan teman-teman,
bahwa suatu ketika datang seorang mahasiswa yang mengaku sangat menyukai
filasafat. Setelah ngobrol “basa-basi” dengannya, tiba-tiba pembicaraan
masuk dalam masalah teologi; secara khusus membahas tentang kehidupan
akhirat. Dan ternyata dalam “otak” mahasiswa tersebut, yang kemudian
dengan sangat “ngotot” ia pertahankan ialah bahwa kehidupan akhirat pada
akhirnya akan “punah”, dan segala sesuatu baik mereka yang ada di surga
maupun yang ada di neraka akan kembali kepada Allah. “Mahasiswa” ini
beralasan karena jika surga dan neraka serta segala sesuatu yang ada di
dalam keduanya kekal maka berarti ada tiga yang kekal, yaitu; Allah,
surga, dan neraka. Dan jika demikian maka menjadi batal-lah definisi
tauhid, karena dengan begitu berarti menetapkan sifat ketuhanan kepada
selain Allah; dalam hal ini sifat kekal (al-Baqâ’).
Kita jawab; Baqâ’ Allah disebut dengan Baqâ’ Dzâty; artinya bahwa Allah
maha Kekal tanpa ada yang ada yang mengekalkan-Nya. Berbeda dengan
kekalnya surga dan neraka; keduanya kekal karena dikekalkan oleh Allah
(Bi Ibqâ-illâh Lahumâ). Benar, secara logika seandainya surga dan neraka
punah dapat diterima, karena keduanya makhluk Allah; memiliki
permulaan, akan tetapi oleh karena Allah menghendaki keduanya untuk
menjadi kekal, maka keduanya tidak akan pernah punah selamanya. Dengan
demikian jelas sangat berbeda antara Baqâ’ Allah dengan Baqâ’-nya surga
dan neraka. Kemudian, dalam hampir lebih dari enam puluh ayat al-Qur’an,
baik yang secara jelas (Sharîh) maupun tersirat, Allah mengatakan bahwa
surga dan neraka serta seluruh apa yang ada di dalam keduanya kekal
tanpa penghabisan. Dan oleh karenanya telah menjadi konsensus (Ijmâ’)
semua ulama dalam menetapkan bahwa surga dan neraka ini kekal selamanya
tanpa penghabisan, sebagaimana dikutip oleh Ibn Hazm dalam Marâtib
al-Ijmâ’, Imam al-Hâfizh Taqiyyuddin as-Subki dalam al-I’tibâr Bi Baqâ’
al-Jannah Wa an-Nâr, dan oleh para ulama terkemuka lainnya.
Dalam pandangan penulis, sebenarnya mahasiswa seperti ini adalah murni
sebagai korban distorsi Ilmu Kalam. Kemungkinan besarnya, ketika ia
masuk ke Perguruan Tinggi, ia merasa bahwa dirinya telah berada di
wilayah “elit” secara ilmiah, ia “demam panggung” dengan iklim wilayah
tersebut, merasa dapat berfikir dan berpendapat sebebas mungkin,
termasuk kebebasan berkenalan dengan berbagai faham teologis. Padahal
ketika awal masuk ke Perguruan Tinggi tersebut ia adalah “botol kosong”
yang tidak memiliki pijakan sama sekali. Akhirnya, karena ia botol
kosong maka seluruh faham masuk di dalam otaknya, termasuk berbagai
aliran faham teologis, tanpa sedikitpun ia tahu manakah di antara
faham-faham tersebut yang seharusnya menjadi pijakan keyakinannya,
padahal -dan ini yang sangat mengherankan-, mahasiswa tersebut kuliah di
fakultas dan jurusan keagamaan. Tentunya lebih miris lagi, ketika
faham-faham teologis yang beragam ini dijamah oleh otak-otak mahasiswa
non-keagamaan. Dan yang penulis sebut terakhir ini adalah realitas yang
benar-benar telah ada di depan mata kita. Karenanya, seringkali kita
melihat mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari jurusan non-keagamaan
mengusung faham-faham teologis yang sangat ekstrim, bahkan seringkali
mereka mengafirkan kelompok apapun di luar kelompok mereka sendiri,
padahal mereka tidak memahami atau bahkan tidak tahu sama sekali apa
yang sedang mereka bicarakan.
• Penulis termasuk cukup aktif “berselancar” di dunia maya, dalam
banyak blog, web, facebook, twitter, dan lainnya sering menuangkan
materi-materi tauhid di atas dasar aqidah Ahlussunnah Wal Jama’ah;
termasuk melakukan dialog dengan beberapa orang yang memiliki faham di
luar keyakinan penulis. Teks-teks mutasyâbihât, baik dari al-Qur’an
maupun hadits-hadits Nabi, yang seharusnya dapat dipahami dengan logika
yang sederhana menjadi bahan yang sangat “hangat”, bahkan cenderung
“panas”; yang dengan sebabnya seringkali terjadi tuduhan “kafir”,
“sesat”, “zindik”, “ilhâd”, dan semacamnya terhadap mereka yang tidak
sepaham. Akibatnya, nama “Ahlussunnah Wal Jama’ah” menjadi “kabur”;
khususnya bagi orang-orang awam yang bukan Ahl at-Tamyîz, hingga mereka
tidak dapat membedakan antara keyakinan tauhid yang suci dengan
keyakinan tasybih (penyerupaan Allah dengan makhluk-Nya) yang jelas
menyesatkan.
Seringkali ketika “berselancar” di internet, penulis berdialog dengan
beberapa orang yang “sangat ngotot” berkeyakinan bahwa Allah bertempat
di atas arsy, lalu –dan ini yang sangat mengherankan– pada saat yang
sama mereka juga ngotot mengatakan bahwa Allah bertempat di langit.
Untuk ini kemudian mereka mengutip beberapa ayat dan hadits yang menurut
mereka sebagai bukti kebenaran aqidah tersebut. Penulis mencoba
menyederhanakan “problem mereka” dengan logika sederhana; “Bukankah arsy
dan langit itu ciptaan Allah? Bila anda berkeyakinan arsy dan langit
itu ciptaan Allah maka berarati menurut anda Allah berubah dari semula
yang ada tanpa langit dan tanpa arsy menjadi bertempat pada kedua
makhluk-Nya tersebut; lalu bukankah perubahan itu menunjukan kebaharuan?
Bukankah pula arsy dan langit itu memiliki bentuk dan ukuran? Lalu anda
sendiri mengatakan bahwa Allah berada di dua tempat; arsy dan langit?”.
Logika-logika sederhana semacam inilah yang sengaja bahkan seringkali
penulis ungkapkan untuk “menyehatkan” akal dan pikiran orang-orang yang
memiliki problem di atas. Tapi alih-alih mereka mau berfikir, namun
ternyata tuduhan “kafir”, “mu’ath-thil” (pengingkar sifat Allah) dan
berbagai tuduhan lainnya yang diterima oleh penulis dari mereka, yang
penulis sendiri tidak tahu persis apakah ungkapan-ungkapan semacam itu
“senjata pamungkas” mereka? Nyatanya memang mereka mengutip beberapa
ayat al-Qur’an dan Hadits-Hadits Nabi untuk dijadikan dasar bagi
keyakinan mereka, masalahnya ialah bahwa ayat-ayat tersebut tidak
dipahami secara komprehensif, tidak dipahami secara kontekstual, dan
bahkan pemahaman mereka jauh berseberangan dengan pemahaman para ulama
terdahulu yang benar-benar kompeten dalam masalah tersebut. Inilah di
antara yang mendorong penulis untuk membukukan buku ini.
• Benar, tulisan ini hanya menyentuh “setitik” persoalan saja dari
lautan Ilmu Kalam, tetapi mudah-mudahan semua yang tertuang di dalamnya
memiliki orientasi dan memberikan pencerahan, paling tidak dalam
beberapa persoalan teologis. Hanya saja titik konsentrasi yang hendak
penulis sampaikan kepada pembaca dari buku ini adalah esensi tauhid
dengan aqidah tanzîh di dalamnya yang diintisarikan dari firman Allah
dalam QS. Asy-Syura: 11; bahwa Allah tidak menyerupai suatu apapun dari
makhluk-Nya. Benar, Ilmu Kalam ini sangat luas, namun bukan untuk
mengabaikan bahasan-bahasan pokok lainnya, penulis memandang bahwa
pembahasan “Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah” untuk saat ini sangat
urgen, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apa yang penulis ungkapkan pada
poin nomor satu di atas tentang menyebarnya aqidah tasybîh benar-benar
sudah sampai kepada batas yang sangat merisihkan dan mengkhawatirkan,
bahkan –meminjam istilah guru-guru penulis– sebuah kondisi “yang tidak
bisa membuat mata tertidur pulas”. Mudah-mudahan materi-materi lainnya
menyangkut berbagai aspek Ilmu Kalam secara formulatif dapat segera
dibukukan dalam bentuk bahasa Indonesia.
Pada dasarnya seluruh apa yang tertuang dalam buku ini bukan barang
baru, dan setiap ungkapan yang tertuang di dalamnya secara orisinil
penulis kutip dari tulisan para ulama dan referensi-referensi yang
kompeten dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, setiap
“klaim”, “kesimpulan”, maupun “serangan” terhadap faham-faham tertentu
di dalam buku ini, semua itu bukan untuk tujuan apapun, kecuali untuk
mendudukan segala persoalan secara proporsional sebagaimana yang telah
dipahami oleh para ulama saleh terdahulu.
• Imam al-Hâfizh Abu Hafsh Ibn Syahin, salah seorang ulama terkemuka
yang hidup sezaman dengan Imam al-Hâfizh ad-Daraquthni (w 385 H),
berkata: “Ada dua orang saleh yang diberi cobaan berat dengan
orang-orang yang sangat buruk dalam aqidahnya. Mereka menyandarkan
aqidah buruk itu kepada keduanya, padahal keduanya terbebas dari aqidah
buruk tersebut. Kedua orang itu adalah Ja’far ibn Muhammad dan Ahmad ibn
Hanbal” .
Orang pertama, yaitu Imam Ja’far ash-Shadiq ibn Imam Muhammad al-Baqir
ibn Imam Ali Zainal Abidin ibn Imam asy-Syahid al-Husain ibn Imam Ali
ibn Abi Thalib, beliau adalah orang saleh yang dianggap oleh kaum Syi’ah
Rafidlah sebagai Imam mereka. Seluruh keyakinan buruk yang ada di dalam
ajaran Syi’ah Rafidlah ini mereka sandarkan kepadanya, padahal beliau
sendiri sama sekali tidak pernah berkeyakinan seperti apa yang mereka
yakini.
Orang ke dua adalah Imam Ahmad ibn Hanbal, salah seorang Imam madzhab
yang empat, perintis madzhab Hanbali. Kesucian ajaran dan madzhab yang
beliau rintis telah dikotori oleh orang-orang Musyabbihah yang mengaku
sebagai pengikut madzhabnya. Mereka banyak melakukan kedustaan-kedustaan
dan kebatilan-kebatilan atas nama Ahmad ibn Hanbal, seperti aqidah
tajsîm, tasybîh, anti takwil, anti tawassul, anti tabarruk, dan lainnya,
yang sama sekali itu semua tidak pernah diyakini oleh Imam Ahmad
sendiri. Terlebih di zaman sekarang ini, madzhab Hanbali dapat dikatakan
telah “hancur” karena dikotori oleh orang-orang yang secara dusta
mengaku sebagai pengikutnya.
Akhirnya, dengan segala keterbatasan dan segala kekurangan yang
terdapat dalam buku ini, penulis serahkan sepenuhnya kepada Allah.
Segala kekurangan dan aib semoga Allah memperbaikinya, dan seluruh
nilai-nilai yang baik dari buku ini semoga menjadi pelajaran yang
bermanfaat bagi seluruh orang Islam. Amin.
Wa Shallallâh Wa Sallam ‘Alâ Rasûlillâh.
Wa al-Hamd Lillâh Rabb al-‘Âlamîn.
Prolog; Latar Belakang
Bab I Kata Istawâ Dalam Tinjauan Terminologis
a. Penyebutan Kata Istawâ,_
b. Definisi Arsy,_
c. Makna Istawâ Dalam Tinjauan Bahasa,_
d. Pembahasan Terminologis,_
e. Istawâ Dalam Makna Istawlâ Dan Qahara,_
f. Tidak Semua Makna Istawlâ atau Qahara Berindikasi Sabq al-Mughâlabah,_
g. Penggunaan Kata “Tsumma” Dalam Beberapa Ayat Tentang Istawâ,_
h. Di Atas Arsy Terdapat Tempat,_
i. Makna Nama Allah “al-‘Alyy” Dan Kata“Fawq” Pada Hak-Nya,_
j. Di antara Ulama Ahlussunnah Dari Kalangan Ulama Salaf Dan Khalaf Yang Mentakwil Istawâ Dengan Istawlâ dan Qahara,_
Bab II Penjelasan Imam Empat Madzhab Tentang Makna Istawa
a. Penjelasan Imam Malik ibn Anas,_
b. Penjelasan Imam Abu Hanifah an-Nu’man ibn Tsabit,_
c. Penjelasan Imam asy-Syafi’i,_
d. Penjelasan Imam Ahmad ibn Hanbal,_
Bab III Jawaban Atas Kerancuan Faham Musyabbihah Dalam Pengingkaran Mereka Terhadap Tafsir Istawâ Dengan Istawlâ
a. Kerancuan Pertama; Pengingkaran Mereka Terhadap Ahli Bahasa,_
b. Kerancuan Kedua; Pemahaman Mereka Tentang Sabq al-Mughâlabah,_
c. Kerancuan ke Tiga; Pengingkaran Mereka Terhadap Sya’ir Tentang Basyr Ibn Marwan,_
d. Kerancuan Ke Empat; Pernyataan Mereka Bahwa Di Dalam Al-Qur’an Tidak Terdapat Penyebutan Kata Istawlâ (Menguasai),_
e. Kerancuan ke Lima; Faedah Penyebutan Arsy Secara Khusus Dalam Ayat-Ayat Tentang Istawâ,_
f. Kerancuan Ke enam; Pengingkaran Mereka Bahwa Tidak Ada Ulama Salaf Yang Mentakwil Istawâ Dengan Istawlâ,_
g. Kerancuan Ke tujuh; Mereka Menyerupakan Sifat Menguasai Basyr Ibn
Marwan Dengan Sifat Menguasai (al-Qahr; al-Istîlâ) Pada Hak Allah,_
h. Kerancuan Ke Delapan; Pernyataan Mereka Bahwa Takwil Istawâ Dengan Istawlâ Adalah Faham Mu’tazilah,_
i. Kerancuan Ke Sembilan; Keyakinan Tasybih Utsaimin Dalam Menyerupakan Istawâ Pada Hak Allah Dengan Istawâ Pada Hak Makhluk,_
j. Kerancuan Ke Sepuluh; Mereka Mengatakan Bahwa Metodologi Takwil Sama Dengan Menafikan Sifat-Sifat Allah,_
Bab III Konsensus Akidah Tanzîh
a. Pernyataan Ulama Bahwa Allah Ada Tanpat Dan Tanpa Arah,_
b. Dalil Akal Kecusian Allah Dari Tempat Dan Arah,_
c. Pernyataan Ulama Ahlussunnah Bahwa Allah Tidak Boleh Dikatakan Berada Di Semua Tempat Atau Ada Di Mana-Mana,_
d. Langit Adalah Kiblat Doa,_
e. Pernyataan Ulama Ahlussunnah Tentang Kekufuran Orang Yang Menetapkan Tempat Bagi Allah,_
Penutup; Epilog_
Daftar Pustaka_
DAFTAR PUSTAKA
al-Qur-ân al-Karîm.
Abbas, Sirajuddin, I’tiqad Ahlusuunah Wal Jama’ah, 2002, Pustaka Tarbiyah, Jakarta
Abadi, al-Fairuz, al-Qâmûs al-Muhîth, Cet. Mu’assasah ar-Risalah, Bairut.
Abidin, Ibn, Radd al-Muhtâr ‘Alâ ad-Durr al-Mukhtâr, Cet. Dar Ihya at-Turats al-‘Arabi, Bairut.
Amidi, al, Saifuddin, Abkâr al-Afkâr,
Ashbahani, al, Abu Nu’aim Ahmad Ibn Abdullah (w 430 H), Hilyah al-Awliyâ’ Wa Thabaqât al-Ashfiyâ’, Dar al-Fikr, Bairut
Ashbahani, al, ar-Raghib al-Ashbahani, Mu’jam Mufradât Gharîb Alfâzh al-Qur-ân, tahqîq Nadim Mar’asyli, Bairut, Dar al-Fikr,
Asqalani, al, Ahmad Ibn Ibn Ali Ibn Hajar, Fath al-Bâri Bi Syarh Shahîh
al-Bukhâri, tahqîq Muhammad Fu’ad Abd al-Baqi, Cairo: Dar al-Hadits,
1998 M
_________, ad-Durar al-Kâminah Fî al-Ayân al-Mi-ah ats-Tsâminah,
Haidarabad, Majlis Da-irah al-Ma’arif al-Utsmaniyyah, cet. 2, 1972.
¬¬¬¬_________, al-Ishâbah Fî Tamyîz ash-Shahâbah, tahqîq Ali Muhammad Bujawi, Bairut, Dar al-Jail, cet. 1, 1992 M
_________, Tahdzîb at-Tahdzîb, Bairut, Dar al-Fikr, 1984 M.
_________, Lisân al-Mîzân, Bairut, Mu’assasah al-Alami Li al-Mathbu’at, 1986 M.
Asakir, Ibn; Abu al-Qasim Ali ibn al-Hasan ibn Hibatillah (w 571 H)
Tabyîn Kadzib al-Muftarî Fîmâ Nusiba Ilâ Imam Abî al-Hasan al-Asy’ari,
Dar al-Fikr, Damaskus.
Asy’ari, al, Ali ibn Isma’il al-Asy’ari asy-Syafi’i (w 324 H), Risâlah
Istihsân al-Khaudl Fî ‘Ilm al-Kalâm, Dar al-Masyari’, cet. 1, 1415
H-1995 M, Bairut
Asy’ari, Hasyim, KH, ‘Aqîdah Ahl as-Sunnah Wa al-Jamâ’ah, Tebuireng, Jombang.
Azdi, al, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy’ats ibn Ishaq as-Sijistani (w
275 H), Sunan Abî Dâwûd, tahqîq Shidqi Muhammad Jamil, Bairut, Dar
al-Fikr, 1414 H-1994 M
Azhari, Isma’il al-Azhari, Mir-ât an-Najdiyyah, India
Baghdadi, al, Abu Manshur Abd al-Qahir ibn Thahir (W 429 H), al-Farq Bayn al-Firaq, Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cet. Tth.
_________, Kitâb Ushûl ad-Dîn, cet. 3, 1401-1981, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Bairut.
¬¬_________, Tafsîr al-Asmâ’ Wa ash-Shifât, Turki.
Balabban, Ibn; Muhammad ibn Badruddin ibn Balabban ad-Damasyqi
al-Hanbali (w 1083 H), al-Ihsân Bi Tartîb Shahîh Ibn Hibbân, Dar
al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Bairut
_________, Mukhtashar al-Ifâdât Fî Rub’i al-‘Ibâdât Wa al-Âdâb Wa Ziyâdât. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, Bairut
Baghdadi, al, Abu Bakar Ahmad ibn Ali, al-Khathib, Târîkh Baghdâd, Bairut, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t. th.
_________, al-Faqîh Wa al-Mutafaqqih, Cet. Dar al-Kutug al-‘Ilmiyyah, Bairut.
Bayjuri, al, Tuhfah al-Murîd Syarh Jawhar at-Tawhîd, Dar Ihya’ at-Turats al-‘Arabi, Indonesia
Bayhaqi, al, Abu Bakar ibn al-Husain ibn ‘Ali (w 458 H), al-Asmâ’ Wa
ash-Shifât, tahqîq Abdullah ibn ‘Amir, 1423-2002, Dar al-Hadits, Cairo.
_________, Syu’ab al-Îmân, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Bairut.
_________, as-Sunan al-Kubrâ, Dar al-Ma’rifah, Bairut. t. th.
Bantani, al, Umar ibn Nawawi al-Jawi, Kâsyifah as-Sajâ Syarh Safînah
an-Najâ, Maktabah Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, Indonesia, th.
_________, Salâlim al-Fudalâ Syarh Manzhûmah Kifâyah al-Atqiyâ’ Ilâ Thariq al-Awliyâ’, Syarikat al-Ma’arif Bandung, t. th.
Bakri, al, As-Sayyid Abu Bakar ibn as-Sayyid Ibn Syatha al-Dimyathi,
Kifâyah al-Atqiyâ’ Wa Minhâj al-Ashfiyâ’ Syarh Hidâyah al-Adzkiyâ’.
Syarikat Ma’arif, Bandung, t. th.
_________, Hâsyiyah I’ânah ath-Thâlibîn ‘Alâ Hall Alfâzh Fath al-Mu’in
Li Syarh Qurrah al-‘Ayn Li Muhimmah ad-Dîn, cet. 1, 1418, 1997, Dar
al-Fikr, Bairut.
Bayyadli, al, Kamaluddin Ahmad al-Hanafi, Isyârât al-Marâm Min ‘Ibârât
Imam, tahqîq Yusuf Abd al-Razzaq, cet. 1, 1368-1949, Syarikah Maktabah
Musthafa al-Halabi Wa Auladuh, Cairo.
Bukhari, al, Muhammad ibn Isma’il, Shahîh al-Bukhâri, Bairut, Dar Ibn Katsir al-Yamamah, 1987 M
Dahlan, Ahmad Zaini Dahlan, al-Futûhât al-Islâmiyyah, Cairo, Mesir, th. 1354 H
_________, ad-Durar as-Saniyyah Fî ar-Radd ‘Alâ al-Wahhâbiyyah, Cet. Musthafa al-Babi al-Halabi, Cairo, Mesir
Dawud, Abu; as-Sijistani, Sunan Abî Dâwûd, Dar al-Janan, Bairut.
Dawud, Abu; ath-Thayalisi, Musnad ath-Thayâlisiy, Cet. Dar al-Ma’rifah, Bairut
Dzahabi, adz-, Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn Utsman, Abu Abdillah,
Siyar A’lâm al-Nubalâ’, tahqîq Syua’ib al-Arna’uth dan Muhammad Nu’im
al-Arqusysyi, Bairut, Mu’assasah ar-Risalah, 1413 H.
_________, Mîzân al-I’tidâl Fî Naqd al-Rijâl, tahqîq Muhammad Mu’awwid
dan Adil Ahmad Abd al-Maujud, Bairut, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cet. 1,
1995 M
_________, an-Nashîhah adz-Dzahabiyyah, Bairut: Dar al-Masyari’, 1419 H-1998 M.
Dimyathi, ad, Abu Bakar as-Sayyid Bakri ibn as-Sayyid Muhammad Syatha
ad-Dimyathi, Kifâyah al-Atqiyâ’ Wa Minhâj al-Ashfiyâ’ Syarh Hidâyah
al-Adzkiyâ’, Bungkul Indah, Surabaya, t. th.
Fayyumi, al, al-Mishbâh al-Munîr, Cet. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Bairut.
Ghazali, al, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ath-Thusi (w
505 H), Kitâb al-Arba’în Fî Ushûl ad-Dîn, cet. 1408-1988, Dar al-Jail,
Bairut
_________, al-Maqshad al-Asnâ Syarh Asmâ’ Allâh al-Husnâ, t. th, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Cairo
_________, Minhâj al-Âbidîn, t. th. Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyyah, Indonesia
_________, Ihyâ’ ‘Ulûm ad-Dîn, Dar al-Fikr, Bairut.
Ghumari, al, as-Sayyid Ahmad ibn Muhammad ash-Shiddiq al-Hasani
al-Maghribi, Abu al-Faidl, al-Mughîr ‘Alâ al-Ahâdîts al-Mawdlû’ah Fî
al-Jâmi’ ash-Shaghîr, cet. 1, t. th. Dar al-‘Ahd al-Jadid
Hanbal, Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad, Dar al-Fikr, Bairut
Haytami, al, Ahmad Ibn Hajar al-Makki, Syihabuddin, al-Fatâwâ al-Hadîtsiyyah, t. th. Dar al-Fikr
_________, al-I’lâm Bi Qawâthi’ al-Islâm, cet. Dar al-Fikr, Bairut
Hakim, al, al-Mustadrak ‘Alâ al-Shahîhayn, Bairut, Dar al-Ma’rifah, t. th.
Habasyi, al, Abdullah ibn Muhammad ibn Yusuf, Abu Abdirrahman,
al-Maqâlât as-Sunniyah Fî Kasyf Dlalâlât Ahmad Ibn Taimiyah, Bairut: Dar
al-Masyari’, cet. IV, 1419 H-1998 M.
_________, asy-Syarh al-Qawîm Fî Hall Alfâzh ash-Shirât al-Mustaqîm, cet. 3, 1421-2000, Dar al-Masyari’, Bairut.
_________, ad-Dalîl al-Qawîm ‘Alâ ash-Shirâth al-Mustaqîm, Thubi’ ‘Ala Nafaqat Ahl al-Khair, cet. 2, 1397 H. Bairut
_________, ad-Durrah al-Bahiyyah Fî Hall Alfâzh al-‘Aqîdah ath-Thahâwiyyah, cet. 2, 1419-1999, Dar al-Masyari’, Bairut.
_________, Sharîh al-Bayân Fî ar-Radd ‘Alâ Man Khâlaf al-Qur-ân, cet. 4, 1423-2002, Dar al-Masyari’, Bairut.
_________, Izh-hâr al-‘Aqîdah as-Sunniyyah Fî Syarh al-‘Aqîdah ath-Thahâwiyyah, cet. 3, 1417-1997, Dar al-Masyari’, Bairut
_________, al-Mathâlib al-Wafiyyah Bi Syarh al-’Aqîdah an-Nasafiyyah, cet. 2, 1418-1998, Dar al-Masyari’, Bairut
_________, at-Tahdzîr asy-Syar’iyy al-Wâjib, cet. 1, 1422-2001, Dar al-Masyari’, Bairut.
Haddad, al, Abdullah ibn Alawi ibn Muhammad, Risâlah al-Mu’âwanah Wa
al-Muzhâharah Wa al-Ma’âzarah, Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah,
Indonesia.
Haramain, al, Imam, Abu al-Ma’ali Abd al-Malik al-Juwaini, al-‘Aqîdah
an-Nizhâmiyyah, ta’lîq Muhammad Zahid al-Kautsari, Mathba’ah al-Anwar,
1367 H-1948 M.
Hayyan, Abu Hayyan al-Andalusi, an-Nahr al-Mâdd Min al-Bahr al-Muhîth, Dar al-Jinan, Bairut.
Hibban, Ibn, ats-Tsiqât, Mu’assasah al-Kutub al-Tsaqafiyyah, Bairut
Hushni, al, Taqiyyuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasyqi ( w
829 H), Kifâyah al-Akhyâr Fî Hall Ghâyah al-Ikhtishâr, Dar al-Fikr,
Bairut. t. th.
_________, Daf’u Syubah Man Syabbah Wa Tamarrad Wa Nasab Dzâlik Ilâ Imam
al-Jalîl Ahmad, al-Maktabah al-Azhariyyah Li at-Turats, t. th.
Imad, al, Ibn; Abu al-Falah ibn Abd al-Hayy al-Hanbali, Syadzarât
adz-Dzahab Fî Akhbâr Man Dzahab, tahqîq Lajnah Ihya al-Turats al-‘Arabi,
Bairut, Dar al-Afaq al-Jadidah, t. th.
Iraqi, al, Zaynuddin Abd ar-Rahim ibn al-Husain, Tharh at-Tatsrîb Fî
Syarh at-Taqrîb, cet. Dar Ihya’ at-Turats al-‘Arabi, Bairut.
Iyadl, Abu al-Fadl Iyyadl ibn Musa ibn ‘Iyadl al-Yahshubi, asy-Syifâ Bi
Ta’rîf Huqûq al-Musthafâ, tahqîq Kamal Basyuni Zaghlul al-Mishri, Isyrâf
Maktab al-Buhuts Wa al-Dirasat, cet. 1421-2000, Dar al-Fikr, Bairut.
Isfirayini, al, Abu al-Mudzaffar (w 471 H), at-Tabshîr Fî ad-Dîn Fî
Tamyîz al-Firqah al-Nâjiyah Min al-Firaq al-Hâlikîn, ta’liq Muhammad
Zahid al-Kautsari, Mathba’ah al-Anwar, cet. 1, th.1359 H, Cairo.
Jailani-al, Abd al-Qadir ibn Musa ibn Abdullah, Abu Shalih al-Jailani, al-Gunyah, Dar al-Fikr, Bairut
Jama’ah, Ibn, Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa’adullah ibn Jama’ah dikenal
dengan Badruddin ibn Jama’ah (w 727 H), Idlâh ad-Dalîl Fi Qath’i Hujaj
Ahl al-Ta’thîl, tahqîq Wahbi Sulaiman Ghawaji, Dar al-Salam, 1410 H-1990
M, Cairo
Jawzi, al, Ibn; Abu al-Faraj Abd ar-Rahman ibn al-Jawzi (w 597 H),
Talbîs Iblîs, tahqîq Aiman Shalih Sya’ban, Cairo: Dar al-Hadits, 1424
H-2003 M
¬¬_________, Daf’u Syubah at-Tasybîh Bi Akaff at-Tanzîh, tahqîq Syaikh
Muhammad Zahid al-Kautsari, Muraja’ah DR. Ahmad Hijazi as-Saqa, Maktabah
al-Kulliyyat al-Azhariyyah, 1412-1991
_________, Zad al-Masîr Fî ‘Ilm at-Tafsîr, Cet. Zuhair asy-Syawisy, Bairut.
Jawziyyah, al; Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, Hâdî al-Arwâh Ilâ Bilâd al-Afrâh, Ramadi Li an-Nasyr, Bairut.
Kalabadzi-al, Muhammad ibn Ibrahim ibn Ya’qub al-Bukhari, Abu Bakar (w
380 H), at-Ta’arruf Li Madzhab Ahl al-Tashawwuf, tahqîq Mahmud Amin
an-Nawawi, cet. 1, 1388-1969, Maktabah al-Kuliyyat al-Azhariyyah Husain
Muhammad Anbabi al-Musawi, Cairo
Katsir, Ibn; Isma’il ibn Umar, Abu al-Fida, al-Bidâyah Wa an-Nihâyah, Bairut, Maktabah al-Ma’arif, t. th.
Kautsari, al, Muhammad Zahid ibn al-Hasan al-Kautsari, Takmilah ar-Radd
‘Alâ Nûniyyah Ibn al-Qayyim, Mathba’ah al-Sa’adah, Mesir.
_________, Maqâlât al-Kawtsari, Dar al-Ahnaf , cet. 1, 1414 H-1993 M, Riyadl.
Khalifah, Haji, Musthafa Abdullah al-Qasthanthini al-Rumi al-Hanafi
al-Mulla, Kasyf al-Zhunûn ‘An Asâmi al-Kutub Wa al-Funûn, Dar al-Fikr,
Bairut.
Khallikan, Ibn; Wafayât al-A’yân, Dar al-Tsaqafah, Bairut
Laknawi, al, Abu al-Hasanat Muhammad Abd al-Hayy al-Laknawi al-Hindi,
ar-Raf’u Wa at-Takmîl Fî al-Jarh Wa at-Ta’dîl, tahqîq Abd al-Fattah Abu
Ghuddah, cet. Dar al-Basya-r al-Islamiyyah, Bairut.
Majah, Ibn, Sunan, cet. al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, Bairut.
Malik, ibn Anas, al-Muwath-tha-, cet. Dar asy-Sya’b, Cairo.
Manzhur, Ibn, al-Ifriqi, Lisân al-‘Arab, cet. Dar Shadir, Bairut.
Maqarri-al, Ahmad al-Maghrirbi al-Maliki al-Asy’ari, Idla-âh al-Dujunnah Fi I’tiqâd Ahl al-Sunnah, Dar al-Fikr, Bairut.
Maturidi, al, Abu Manshur, Kitâb al-Tawhîd, Dar al-Masyriq, Bairut
Malibari, al, Zainuddin Ibn Ali, Nadzm Hidâyah al-Adzkiyâ’, Syirkah Bukul Indah, Surabaya, t. th.
Makki, al, Tajuddin Muhammad Ibn Hibatillah al-Hamawi, Muntakhab Hadâ-iq
al-Fushûl Wa Jawâhir al-Ushûl Fî ‘Ilm al-Kalâm ‘Alâ Ushul Abî al-Hasan
al-Asy’ari, cet, 1, 1416-1996, Dar al-Masyari’, Bairut
Mayyarah, Ahmad Mayyarah, ad-Durr at-Tsamîn Wa al-Mawrid al-Mu’în Syarh
al-Mursyid al-Mu’în ‘Alâ adl-Dlarûriyy Min ‘Ilm ad-Dîn, cet. Dar
al-Fikr, Bairut.
Mizzi, al, Tahdzîb al-Kamâl Fî Asmâ’ ar-Rijâl, Mu’assasah ar-Risalah, Bairut.
Mutawalli, al, al-Ghunyah Fî Ushûl ad-Din, Mu’assasah al-Kutub ats-Tsaqafiyyah, Bairut.
Muslim, Muslim ibn al-Hajjaj, Shahîh Muslim, Cat. Dar Ihya at-Turats al-‘Arabi, Bairut.
Nabhani, al, Yusuf Isma’il, Jâmi’ Karâmât al-Awliyâ’, Dar al-Fikr, Bairut
Naisaburi, al, Muslim ibn al-Hajjaj, al-Qusyairi (w 261 H), Shahîh
Muslim, tahqîq Muhammad Fu’ad Abd al-Baqi, Bairut, Dar Ihya’ al-Turats
al-‘Arabi, 1404
Nawawi, al, Yahya ibn Syaraf, Muhyiddin, Abu Zakariya, al-Minhâj Bi
Syarh Shahîh Muslim Ibn al-Hajjâj, Cairo, al-Maktab ats-Tsaqafi, 2001 H.
_________, Rawdlah at-Thâlibîn, cet. Dar al-Fikr, Bairut.
Najdi, an, Muhammad ibn Humaid an-Najdi, as-Suhub al-Wâbilah ‘Alâ Dlarâ-ih al-Hanâbilah, Cet. Maktabah Imam Ahmad.
Qari, al, Ali Mulla al-Qari, Syarh al-Fiqh al-Akbar, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Bairut
Qadli, al, Samir, Mursyid al-Hâ-ir Fî Hall Alfâzh Risâlah Ibn ‘Asâkir, cet. I, 1414 H-1994 M, Dar al-Masyari’, Bairut
Qath-than, Ibn, Abu al-Hasan Ali ibn al-Qath-than (w 628 H), an-Nazhar
Fî Ahkâm an-Nazhar Bi Hâssah al-Bashar, tahqîq Muhammad Abu al-Ajfan,
Cet. Maktabah at-Taubah, Riyadl
Qusyairi, al, Abu al-Qasim Abd al-Karim ibn Hawazan an-Naisaburi,
ar-Risâlah al-Qusyairiyyah, tahqîq Ma’ruf Zuraiq dan ‘Ali Abd al-Hamid
Balthahji, Dar al-Khair.
Qurthubi, al, al-Jâmi’ Li Ahkâm al-Qur’ân, Dar al-Fikr, Bairut
Rifa’i, ar, Abu al-Abbas Ahmad ar-Rifa’i al-Kabîr ibn al-Sulthan Ali,
Maqâlât Min al-Burhân al-Mu’ayyad, cet. 1, 1425-2004, Dar al-Masyari’,
Bairut.
Razi, ar, Fakhruddin ar-Razi, at-Tafsîr al-Kabîr Wa Mafâtîh al-Ghayb, Dar al-Fikr, Bairut
Sarraj, as, Abu Nashr, Al-Luma’, tahqîq Abd al-Halim Mahmud dan Thaha
Abd al-Baqi Surur, Maktabah ats-Tsaqafah al-Diniyyah, Cairo Mesir
Syafi’i, asy, Muhammad ibn Idris ibn Syafi’ (w 204 H), al-Kawkab
al-Azhar Syarh al-Fiqh al-Akbar, al-Maktabah al-Tijariyyah Mushthafa
Ahmad al-Baz, Mekah, t. th.
Sya’rani, as, Abd al-Wahhab, ath-Thabaqat al-Qubra, Maktabah al-Taufiqiyyah, Amam Bab al-Ahdlar, Cairo Mesir.
_________, al-Yawâqît Wa al-Jawâhir Fî Bayân ‘Aqâ-id al-Akâbir, t. th, Mathba’ah al-Haramain.
_________, al-Kibrît al-Ahmar Fî Bayân ‘Ulum asy-Syaikh al-Akbar, t. th, Mathba’ah al-Haramain.
_________, al-Anwâr al-Qudsiyyah al-Muntaqat Min al-Futûhât al-Makkiyyah, Bairut, Dar al-Fikr, t. th.
_________, Lathâ-if al-Minan Wa al-Akhlâq, Alam al-Fikr, Cairo
Subki, as, Taqiyyuddin Ali ibn Abd al-Kafi as-Subki, as-Sayf ash-Shaqîl Fî ar-Radd ‘Alâ Ibn Zafîl, Mathba’ah al-Sa’adah, Mesir.
_________, ad-Durrah al-Mudliyyah Fî ar-Radd ‘Alâ Ibn Taimiyah, dari
manuskrif Muhammad Zahid al-Kautsari, cet. Al-Qudsi, Damaskus, Siria,
th. 1347
_________, al-I’tibâr Bi Baqâ’ al-Jannah Wa an-Nâr, dari manuskrif
Muhammad Zahid al-Kautsari, cet. Al-Qudsi, Damaskus, Siria, th. 1347
Subki, as, Tajuddin Abd al-Wahhab ibn Ali ibn Abd al-Kafi as-Subki,
Thabaqât asy-Syâfi’iyyah al-Kubrâ, tahqîq Abd al-Fattah dan Mahmud
Muhammad ath-Thanahi, Bairut, Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyyah.
Subki, as, Mahmud, Ithâf al-Kâ-inât Bi Bayân Madzhab as-Salaf Wa al-Khalaf Fi al-Mutasyâbihât, Mathba’ah al-Istiqamah, Mesir
Suhrawardi, as, Awârif al-Ma’ârif, Dar al-Fikr, Bairut
Syakkur, asy, Abd, Senori, KH, al-Kawâkib al-Lammâ’ah Fî Bayân ‘Aqîdah Ahl al-Sunnah Wa al-Jamâ’ah
Syahrastani, asy, Muhammad Abd al-Karim ibn Abi Bakr Ahmad, al-Milal Wa
an-Nihal, ta’lîq Shidqi Jamil al-‘Athar, cet. 2, 1422-2002, Dar al-Fikr,
Bairut.
Sulami, as, Abu Abd ar-Rahman Muhammad Ibn al-Husain (w 412 H), Thabaqât
ash-Shûfiyyah, tahqîq Musthafa Abd al-Qadir Atha, Mansyurat Ali
Baidlun, cet. 2, 1424-2003, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Bairut.
Suyuthi, as, Jalaluddin Abd ar-Rahman ibn Abi Bakr, al-Hâwî Li al-Fatâwî, cet. 1, 1412-1992, Dar al-Jail, Bairut.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬_________, ad-Durr al-Mantsûr Fî at-Tafsîr al-Ma’tsûr, Dar al-Fikr, Bairut.
Tabban, Arabi (Abi Hamid ibn Marzuq), Barâ-ah al-Asy’ariyyîn Min ‘Aqâ-id
al-Mukhâlifîn, Mathba’ah al-‘Ilm, Damaskus, Siria, th. 1968 M-1388 H
Taimiyah, Ibn; Ahmad ibn Taimiyah, Minhâj as-Sunnah an-Nabawiyyah, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Bairut.
¬¬¬_________, Muwâfaqah Sharîh al-Ma’qûl Li Shahîh al-Manqûl, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Bairut.
_________, Syarh Hadîts an-Nuzûl, Cet. Zuhair asy-Syawisy, Bairut.
_________, Majmû Fatâwâ, Dar ‘Alam al-Kutub, Riyadl.
_________, Naqd Marâtib al-Ijmâ’ Li Ibn Hazm, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Bairut.
_________, Bayân Talbîs al-Jahmiyyah, Mekah.
Thabari, ath, Târîkh al-Umam Wa al-Mulûk, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Bairut.
_________, Tafsîr Jâmi’ al-Bayân ‘An Ta-wîl Ây al-Qur-ân, Dar al-Fikr, Bairut
Tim Pengkajian Keislaman Pada Jam’iyyah al-Masyari al-Khairiyyah
al-Islamiyyah, al-Jawhar ats-Tsamîn Fî Ba’dl Man Isytahar Dzikruh Bayn
al-Muslimîn, Bairut, Dar al-Masyari’, 1423 H, 2002 M.
_________, at-Tasyarruf Bi Dzikr Ahl at-Tashawwuf, Bairut, Dar al-Masyari, cet. I, 1423 H-2002 M
Thabarani, ath, Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayyub, Abu Sulaiman (w 360 H),
al-Mu’jam ash-Shagîr, tahqîq Yusuf Kamal al-Hut, Bairut, Muassasah
al-Kutuh al-Tsaqafiyyah, 1406 H-1986 M.
_________, al-Mu’jam al-Awsath, Bairut, Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiyyah.
_________, al-Mu’jam al-Kabîr, Bairut, Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiyyah.
Tirmidzi, at, Muhammad ibn Isa ibn Surah as-Sulami, Abu Isa, Sunan at-Tirmidzi, Bairut, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t. th.
Zabidi, az, Muhammad Murtadla al-Husaini, Ithâf as-Sâdah al-Muttaqîn Bi Syarh Ihyâ’ Ulûm al-Dîn, Bairut, Dar at-Turats al-‘Arabi
¬¬_________, Tâj al-‘Arûs Syarh al-Qâmûs, Cet. al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, Bairut.
Zurqani, az, Abu Abdillah Muhammad ibn Abd al-Baqi az-Zurqani (w 1122
H), Syarh az-Zurqâni ‘Alâ al-Muwatha’, Dar al-Ma’rifah, Bairut.
Data Penyusun
H. Kholilurrohman Abu Fateh, Lc, MA, lahir di Subang 15 November
1975, Dosen Unit Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta (DPK/Diperbantukan di STAI Al-Aqidah al-Hasyimiyyah
Jakarta). Jenjang pendidikan formal dan non formal, di antaranya;
Pondok Pesantren Daarul Rahman Jakarta (1993), Institut Islam Daarul
Rahman (IID) Jakarta (S1/Syari’ah Wa al-Qanun) (1998), STAI az-Ziyadah
Jakarta (S1/Ekonomi Islam) (2002), Pendidikan Kader Ulama (PKU) Prop.
DKI Jakarta (2000), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (S2/Tafsir dan
Hadits) (2005), Tahfîzh al-Qur’an di Pondok Pesantren Manba’ul Furqon
Leuwiliang Bogor (Non Intensif), “Ngaji face to face” (Tallaqqî Bi
al-Musyâfahah) untuk mendapatkan sanad beberapa disiplin ilmu kepada
beberapa Kiyai dan Haba-ib di wilayah Jawa Barat, Banten, dan khususnya
di wilayah Prop. DKI Jakarta. Khâdim pada Syabab Ahlussunnah Wal Jama’ah
(Syahamah) Jakarta, sebuah organisasi yang aktif membela aqidah
Ahlussunnah Wal Jama’ah; al-Asy’ariyyah dan al-Maturidiyyah. Selain
sebagai dosen juga mengajar di beberapa Pondok Pesantren dan memimpin
beberapa Majalis ‘Ilmiyyah di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sekarang
tengah menyelesaikan jenjang S3 (Doktor) di UIN Syarif Haidayatullah
Jakarta pada konsentrasi Tafsir Dan Hadits.
Ijâzah sanad (mata rantai) keilmuan yang telah didapat di antaranya;
dalam seluruh karya Syekh Nawawi al-Bantani dari KH. Abdul Jalil (Senori
Tuban); dari KH. Ba Fadlal; dari KH. Abdul Syakur; dari Syekh Nawawi
Banten. KH. Ba Fadlal selain dari KH. Abdul Syakur, juga mendapat sanad
dari KH. Hasyim Asy’ari (Tebuireng); dari Syekh Nawawi Banten.
Kemudian dalam seluruh disiplin ilmu Islam; mendapatkan Ijâzah ‘Âmmah
dari KH. Abdul Hannan Ma’shum (Kediri); dari KH. Abu Razin Muhammad
Ahmad Sahal Mahfuzh (Pati); dari KH. Zubair ibn Dahlan (Sarang) dan
al-Musnid Syekh Yasin al-Padani. Secara khusus; Syekh Yasin al-Padani
telah membukukan seluruh sanad beliau (ats-Tsabt) di antaranya dalam
kitab “al-‘Iqd al-Farîd Min Jawâhir al-Asânîd”.